Sunda/Galuh nu Agung : Galunggung, GARUT

Kesalah-kaprahan dalam memahami “Sunda”
sebagai nama sebuah suku bangsa atau kelompok masyarakat yang tinggal
di pulo Jawa bagian Barat telah berakibat fatal dan tragis terhadap
keberadaan nama “Galuh”.
“Galuh” adalah nama bangsa yang menganut ajaran / agama “Sunda”.
Dengan demikian yang selama ini selalu disebut “Orang Sunda” sebagai
kelompok kesukuan atau kemasyarakatan maksud yang sebenarnya adalah
“Orang Galuh” atau “Bangsa Galuh Agung” (tepatnya menunjuk kepada
penduduk wilayah Rama), sebab sangat mustahil orang yang menganut agama
Sunda sekaligus mengaku beragama Islam atau Kristiani atau Hindu atau
Buddha, ataupun yang lainnya.

Agar
lebih jelas kita gunakan contoh sebagai berikut; jika seseorang
mengatakan “Saya orang Indonesia beragama Islam” (*Islam = Selamat)
pernyataan itu sering disingkat menjadi “Saya orang Islam”. Lain hal
jika kalimatnya berbunyi “Saya bangsa Indonesia menganut agama Islam”,
dalam kalimat tersebut jelas mengatakan status kebangsaannya, dan memang
tidak ada “bangsa Islam” di Indonesia sebab yang layak disebut “bangsa
Islam” tentunya hanya bangsa Arab itu sendiri. Maka demikian pula dengan
persoalan Sunda dan Galuh, hingga dengan sewajarnya jika mengatakan
bahwa “Saya orang Galuh beragama Sunda”.
“Galuh” sama sekali bukan daerah kecil yang terletak di daerah
Ciamis. Pada jaman dahulu luas wilayah Galuh hampir sama dengan luas
Bumi atau boleh jadi hampir sama dengan luas keberadaan ajaran Sunda
(Matahari).
Penyebaran ajaran Sunda di wilayah Galuh Hyang Agung
Di Eropa, khususnya wilayah Perancis dan sekitarnya nama atau sebutan “Galuh” lebih dikenal sebagai “Gaul” (Gaulia/ Golia/ Bangsa Gaul) dan lebih umum sering disebut sebagai bangsa Gallia. Sedangkan di wilayah Timur-Tengah tepatnya di Israel istilah “Galuh” dikenal dengan sebutan “Galillea” (Galilee).
Untuk membuktikannya kita perlu memahami peninggalan sejarah di
beberapa negara yang secara prinsip hampir tidak ada bedanya dengan yang
ada di Indonesia dan khususnya di pulo Jawa.
Ajaran bangsa Galuh yaitu Sundayana ataupun Surayana sangat kental dengan kehidupan masyarakat daerah Timur-Tengah (Israel) tepatnya di daerah “Galillea”.
Pada mulanya kedatangan ajaran Sunda tentu saja ditentang oleh
masyarakat lokal (Israel – Palestina), kejadian tersebut diabadikan
dalam cerita David (Nabi Daud) melawan Goliath yang dikalahkan oleh
sebuah “batu”, dan batu yang dimaksud adalah “lingga/ menhir atau batu
satangtung”.
Kewilayahan Galuh Agung penganut ajaran
Sunda (Matahari) dimasa lalu pada umumnya terdapat beberapa penanda
sebagai perlambangan yaitu berupa; Batu Menhir (Lingga), Matahari,
Simbol Ayam ataupun burung dan Terdapat simbol Sapi atau Kerbau atau
sejenisnya.
1. MENHIR / LINGGA / BATU SATANGTUNG

Menhir (Lingga)
Lingga adalah sebuah “batu” penanda yang diletakan sebagai “pusat” kabuyutan, masyarakat Jawa Barat sering menyebutnya sebagai “Batu Satangtung”
dan merupakan penanda wilayah RAMA. Bentuk menhir (lingga) di beberapa
negara yang tidak memiliki batu alam utuh dan besar pada umumnya
digantikan oleh ‘tugu batu’ buatan seperti yang terdapat di Mekah dan
Vatican.


Lingga sebagai batu kabuyutan berasal dari kata “La-Hyang-Galuh”
(Hukum Leluhur Galuh). Maksud perlambangan Lingga sesungguhnya lebih
ditujukan sebagai pusat/ puseur (inti) pemerintahan di setiap wilayah
Ibu Pertiwi, tentu saja setiap bangsa memiliki Ibu Pertiwi-nya
masing-masing (Yoni).
Dari tempat Lingga (wilayah Rama) inilah
lahirnya kebijakan dan kebajikan yang kelak akan dijalankan oleh para
pemimpin negara (Ratu). Hal ini sangat berkaitan erat dengan
ketata-negaraan bangsa Galuh dalam ajaran Sunda, dimana Matahari menjadi
pusat (saka) peredaran benda-benda langit. Fakta yang dapat kita temui
pada setiap negara (kerajaan) di dunia adalah adanya kesamaan pola
ketatanegaraan yang terdiri dari Rama (Manusia Agung), Ratu (‘Maharaja’)
dan Rasi (raja-raja kecil/ karesian) dan konsep ini kelak disebut
sebagai Tri-Tangtu atau Tri-Su-La-Naga-Ra.
Umumnya sebuah Lingga diletakan dalam
formasi tertentu yang menunjukan ke-Mandala-an, yaitu tempat sakral yang
harus dihormati dan dijaga kesuciannya. Mandala lebih dikenal oleh masyarakat dunia dengan sebutan Dolmen yang tersebar hampir di seluruh penjuru dunia, di Perancis disebut sebagai Mandale sedangkan batunya (lingga) disebut Obelisk ataupun Menhir.

Mandala (tempat suci) secara prinsip terdiri dari 5 lingkaran
berlapis yang menunjukan batas kewilayahan atau tingkatan (secara
simbolik) yaitu;
1. Mandala Kasungka
2. Mandala Seba
3. Mandala Raja
4. Mandala Wangi
5. Mandala Hyang (inti lingkaran berupa ‘titik’ Batu Satangtung)
Ke-Mandala-an merupakan rangkaian konsep menuju kosmos yang berasal
dari pembangunan kemanunggalan diri terhadap negeri, kemanunggalan
negeri terhadap bumi, dan kemanunggalan bumi terhadap langit “suwung”
(ketiadaan). Dalam bahasa populer sering disebut sebagai perjalanan dari
“mikro kosmos menuju makro kosmos” (keberadaan yang pernah ada dan
selalu ada).

 2. LAMBANG AYAM / HAYAM
2. LAMBANG AYAM / HAYAM
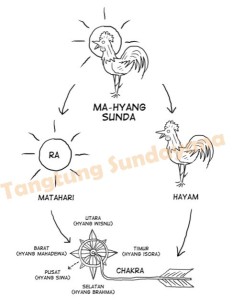
Ayam atau Hayam merupakan perlambangan atas dimulainya sebuah
kehidupan. Dalam hal ini keberadaan sosok ayam sangat erat kaitannya
dengan kehadiran Matahari. Ayam adalah siloka (symbol) para pendahulu
yang memulai kehidupan (leluhur) dan bangsa Galuh menyebut para
leluhurnya sebagai “Hyang”, maksudnya,,,
bersambung,,,

Tabe pun,
TANGTUNG SUNDAYANA
Sumber:
http://ncepborneo.wordpress.com/2013/09/16/galuh-agung/
RaHayu _/\_
Sampurasun,,,
Berdasarkan “Sastrajenrahayuningrat” istilah “Sunda” dibentuk oleh
tiga suku kata yaitu SU-NA-DA yang artinya adalah “matahari” ;
- SU = Sejati/ Abadi
- NA = Api
- DA = Besar/ Gede/ Luas/ Agung
Dalam kesatuan kalimat “Sunda” mengandung arti “Sejati-Api-Besar” atau “Api Besar
yang Sejati atau bisa juga berarti Api Agung
yang Abadi”. Maksud dan maknanya adalah matahari atau “Sang Surya”
(Panon Poe/ Mata Poe/ Sang Hyang Manon). Sedangkan kata “Sastrajenrahayuningrat”
(Su-Astra-Ajian-Ra-Hayu-ning-Ratu) memiliki arti sebagai berikut;
- Su = Sejati/ Abadi
- Astra = Sinar/ Penerang
- Ajian = Ajaran
- Ra = Matahari (Sunda)
- Hayu = Selamat/ Baik/ Indah
- ning = dari
- Ratu = Penguasa (Maharaja)
Dengan demikian “Sastrajenrahayuningrat” jika diartikan secara bebas
adalah “Sinar Sejati Ajaran Matahari – Kebaikan dari Sang Ratu” atau
“Penerang
yang Abadi Ajaran Matahari – Kebaikan dari Sang Maharaja” atau boleh jadi maksudnya ialah “Sinar Ajaran Matahari Abadi
atas Kebaikan dari Sang Penguasa/ Ratu/ Maharaja Nusantara”, dst.
“Sunda” sama sekali bukan nama etnis/ ras/ suku yang tinggal di pulo
Jawa bagian barat dan bukan juga nama daerah, karena
sesungguhnya “Sunda” adalah nama ajaran atau agama tertua di muka Bumi,
keberadaannya jauh sebelum ada jenis agama apapun yang dikenal pada saat
sekarang.
Agama “Sunda” merupakan cikal-bakal ajaran tentang “cara hidup
sebagai manusia beradab hingga mencapai puncak kemanusiaan yang
tertinggi (adi-luhung). Selain itu agama Sunda juga yang mengawali
lahirnya sistem pemerintahan dengan pola
karatuan (kerajaan) yang pertama di dunia, terkenal dengan konsep SITUMANG
(Rasi-Ratu-Rama-Hyang) dengan perlambangan “anjing” (tanda kesetiaan).
Ajaran/ agama Sunda (Matahari) pada mulanya disampaikan oleh
Sang Sri Rama Mahaguru Ratu Rasi Prabhu Shindu La-Hyang (Sang Hyang Tamblegmeneng) putra dari
Sang Hyang Watu Gunung Ratu Agung Manikmaya yang lebih dikenal sebagai
Aji Tirem (Aki Tirem) atau
Aji Saka Purwawisesa.
Ajaran Sunda lebih dikenal dengan sebutan
Sundayana (
yana =
way of life,
aliran, ajaran, agama) artinya adalah “ajaran Sunda atau agama
Matahari” yang dianut oleh bangsa Galuh, khususnya di Jawa Barat.
Sundayana disampaikan secara turun-temurun dan menyebar ke seluruh dunia melalui para Guru Agung (Guru Besar/
Batara Guru), masyarakat Jawa-Barat lebih mengenalnya dengan sebutan
Sang Guru Hyang atau “Sangkuriang” dan sebagian lagi memanggilnya dengan sebutan
“Guriang” yang artinya
“Guru Hyang” juga.
Landasan inti ajaran Sunda adalah
“welas-asih” atau cinta-kasih, dalam bahasa Arab-nya disebut
“rahman-rahim”, inti ajaran inilah yang kelak berkembang menjadi pokok ajaran seluruh agama yang ada sekarang, sebab adanya rasa
welas-asih ini
yang menjadikan seseorang layak disebut sebagai manusia. Artinya, dalam
pandangan agama Sunda (bangsa Galuh) jika seseorang tidak memiliki
rasa
welas-asih maka ia tidak layak untuk disebut manusia, pun tidak layak disebut binatang, lebih tepatnya sering disebut sebagai
Duruwiksa (Buta) mahluk biadab.
Agar pemahaman ke depan tidak menjadi rancu dan membingungkan dalam
memahami istilah “Sinar (Astra/ Ra/ Matahari), Cahaya (Dewa) dan Terang”
maka perlu dijelaskan sebagai berikut;
 Sundayana
Sundayana terbagi dalam tiga bidang ajaran dalam satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah (Kemanunggalan) yaitu;
- Tata-Salira/ Kemanunggalan Diri; berisi tentang
pembentukan kualitas manusia yaitu, meleburkan diri dalam “ketunggalan”
agar menjadi “diri sendiri” (si Swa) yang beradab, merdeka dan
berdaulat atau menjadi seseorang yang tidak tergantung kepada apapun dan
siapapun selain kepada diri sendiri.
- Tata-Naga-Ra/ Kemanunggalan Negeri; yaitu
memanunggalkan masyarakat/ bangsa (negara) dalam berkehidupan di Bumi
secara beradab, merdeka dan berdaulat. Pembangunan negara yang mandiri,
tidak menjajah dan tidak dijajah.
- Tata-Buana/ Kemanunggalan Bumi; ialah kebijakanuniversal (kesemestaan) untuk memanunggalkan Bumi dengan segala isinya dalam semesta kehidupan agar tercipta kedamaian hidup di Buana.
Sesuai dengan bentuk dan dasar pemikiran ajaran Matahari sebagai
sumber cahaya maka tata perlambangan wilayah di sekitar Jawa-Barat
banyak yang mempergunakan sebutan
“Ci”yang artinya “Cahaya”
, dalam bahasa India disebut sebagai
deva/ dewa (cahaya) yaitu pancaran (gelombang) yang lahir dari Matahari berupa warna-warna. Terdapat lima warna cahaya utama
(Pancawarna) yang menjadi landasan filosofi kehidupan bangsa Galuh penganut ajaran Sunda:
- Cahaya Putih di timur disebut Purwa, tempat Hyang Iswara.
- Cahaya Merah di selatan disebut Daksina, tempat Hyang Brahma.
- Cahaya Kuning di barat disebut Pasima, tempat Hyang Mahadewa.
- Cahaya Hitam di utara disebut Utara, tempat Hyang Wisnu.
- Segala Warna Cahaya di pusat disebut Madya, tempat Hyang Siwa.
Lima kualitas “Cahaya” tersebut sesungguhnya merupakan nilai “waktu” dalam hitungan
“wuku”. Kelima
wuku (
wuku lima)
tidak ada yang buruk dan semuanya baik, namun selama ini Sang Hyang
Siwa (pelebur segala cahaya/ warna) telah disalah-artikan menjadi “dewa
perusak”, padahal arti kata “pelebur” itu adalah “pemersatu” atau yang
meleburkan atau memanunggalkan. Jadi, sama sekali tidak terdapat ‘dewa’
yang bersifat merusak dan menghancurkan.
Ajaran Sunda dalam silib-siloka “Panah Chakra”
“Ajaran Sunda” di dalam cerita pewayangan dilambangkan dengan
Jamparing Panah Chakra,
yaitu ‘raja segala senjata’ milik Sang Hyang Wisnu yang dapat
mengalahkan sifat jahat dan angkara-murka, tidak ada yang dapat lolos
dari bidikan
Jamparing Panah Chakra. Maksudnya adalah;
- Jamparing =
Jampe Kuring
- Panah =
Manah = Hati (Rasa
Welas-Asih)
-
Chakra atau
Cakra = Titik Pusaran yang bersinar/ Roda Penggerak Kehidupan (‘matahari’).
- Secara simbolik gendewa
(gondewa) merupakan bentuk bibir yang sedang tersenyum (?).
Panah Chakra di Jawa Barat biasa disebut sebagai
“Jamparing Asih” maksudnya adalah
“Ajian Manah nu Welas Asih” (ajian hati yang lembut penuh dengan cinta-kasih). Dengan demikian maksud utama dari
Jamparing Panah Chakra atau
Jamparing Asih itu ialah “ucapan yang keluar dari hati yang
welas asih dapat menggerakan roda kehidupan yang bersinar”.
Keberadaan Panca Dewa kelak disilib-silokakan (diperlambangkan) ke
dalam kisah “pewayangan” dengan tokoh-tokoh baru melalui kisah
Ramayana (Ajaran Rama) serta kisah
Mahabharata pada tahun +/-1500 SM;
Yudis-ti-Ra, Bi-Ma, Ra-ju-Na, Na-ku-La, dan Sa-Dewa. Kelima cahaya itu kelak dikenal dengan sebutan
“Pandawa” singkatan
dari “Panca Dewa” (Lima Cahaya) yang merupakan perlambangan atas
sifat-sifat kesatria negara. Istilah “wayang” itu sendiri memiliki arti
“bayang-bayang”, maksudnya adalah perumpamaan dari kelima cahaya
tersebut di atas.
Selama ini cerita wayang selalu dianggap ciptaan bangsa India, hal
tersebut mungkin “benar” tetapi boleh jadi “salah”. Artinya kemungkinan
terbesar adalah bangsa India telah berjasa melakukan pencatatan tentang
kejadian besar yang pernah ada di Bumi Nusantara melalui kisah
pewayangan dalam cerita epos
Ramayana dan
Mahabharata. Logika sederhananya adalah; India dikenal sebagai bangsa
Chandra (Chandra Gupta) sedangkan Nusantara dikenal sebagai bangsa Matahari
(Ra-Hyang),
dalam hal ini tentu Matahari lebih unggul dan lebih utama ketimbang
Bulan. India diterangi atau dipengaruhi oleh ajaran dan kebudayaan
Nusantara. Namun demikian tidak dapat disangkal bahwa bukti (jejak)
peninggalan yang maha agung itu di Bumi Nusantara telah banyak
dilupakan, diselewengkan hingga dimusnahkan oleh bangsa Indonesia
sendiri sehingga pada saat ini kita sulit untuk membuktikannya melalui
“kebenaran ilmiah”.
Berkaitan dengan persoalan
“Pancawarna”, bagi orang-orang yang lupa kepada “jati diri” (sebagai bangsa Matahari) di masyarakat Jawa-Barat dikenal peribahasa
“teu inget ka Purwa Daksina…!” artinya
adalah “lupa kepada Merah-Putih” (lupa akan kebangsaan/ tidak tahu
diri/ tidak ingat kepada jati diri sebagai bangsa Galuh penganut ajaran
Sunda).
Banyak orang Jawa Barat mengaku dirinya sebagai orang “Sunda”, mereka
mengagungkan “Sunda” sebagai genetika biologis dan budayanya yang
membanggakan, bahkan secara nyata perilaku diri mereka yang lembut telah
menunjukan
kesundaannya(sopan-santun dan berbudhi), namun unik
dan anehnya mereka ‘tidak mengakui’ bahwa itu semua adalah hasil
didikan Agama Sunda yang telah mereka warisi dari para leluhurnya secara
turun-temurun, seolah telah menjadi
genetika religi pada diri manusia Galuh.
Masyarakat Jawa Barat tidak menyadari (tidak mengetahui) bahwa
perilaku lembut penuh tata-krama sopan-santun dan berbudhi itu terjadi
akibat adanya “ajaran” (agama Sunda) yang mengalir di dalam darah mereka
dan bergerak tanpa disadari
(refleks). Untuk mengatakan kejadian tersebut para leluhur menyebutnya sebagai;
“nyumput buni di nu caang” (tersembunyi ditempat yang
terang) artinya adalah; mentalitas, pikiran, perilaku, seni, kebudayaan,
filosofi dll. yang mereka lakukan sesungguhnya adalah hasil didikan
agama Sunda tetapi si pelaku sendiri tidak mengetahuinya.
Inti pola dasar ajaran Sunda adalah “berbuat baik dan benar yang dilandasi oleh kelembutan rasa
welas-asih”. Pola dasar tersebut diterapkan melalui
Tri-Dharma (Tiga Kebaikan) yaitu sebagai pemandu ‘ukuran’ nilai atas keagungan diri seseorang/ derajat manusia diukur berdasarkan
dharma (kebaikan) :
- Dharma Bakti, ialah seseorang yang telah
menjalankan budhi kebaikan terhadap diri, keluarga serta di lingkungan
kecil tempat ia hidup, manusianya bergelar “Manusia Utama”.
- Dharma Suci, ialah seseorang yang telah menjalankan
budhi kebaikan terhadap bangsa dan negara, manusianya bergelar “Manusia
Unggul Paripurna” (menjadi idola).
- Dharma Agung, ialah seseorang yang telah
menjalankan budhi kebaikan terhadap segala peri kehidupan baik yang
terlihat maupun yang tidak terlihat, yang tercium, yang tersentuh dan
tidak tersentuh, segala kebaikan yang tidak terbatasi oleh ruang dan
waktu, manusianya bergelar “Manusia Adi Luhung” (Batara Guru)
Nilai-nilai yang terkandung di dalam
Tri-Dharma ini kelak menjadi pokok ajaran “Budhi-Dharma”
(Buddha) yang mengutamakan budhi kebaikan sebagai bukti dan bakti rasa
welas-asih terhadap segala kehidupan untuk mencapai kebahagiaan, atau pembebasan diri dari kesengsaraan.
Ajaran ini kelak dilanjutkan dan dikembangkan oleh salah seorang tokoh
Mahaguru Rasi Shakyamuni – Sidharta Gautama (‘Sang Budha’), seorang putra mahkota kerajaan Kapilawastu di Nepal – India.
Pembentukan
Tri-Dharma Sunda dilakukan melalui tahapan yang berbeda sesuai dengan tingkatan umurnya (?) yaitu :
- Dharma Rasa, ialah mendidik diri untuk dapat memahami “rasa” (kelembutan) di dalam segala hal, sehingga mampu menghadirkan keadaan “ngarasa jeung rumasa” (menyadari
rasa dan memahami perasaan). Dengan demikian dalam diri seseorang kelak
muncul sifat menghormati, menghargai, dan kepedulian terhadap sesama
serta kemampuan merasakan yang dirasakan oleh orang lain (pihak lain),
hal ini merupakan pola dasar pembentukan sifat “welas-asih” dan manusianya kelak disebut “Dewa-Sa”.
- Dharma Raga, adalah mendidik diri dalam bakti nyata
(bukti) atau mempraktekan sifat rasa di dalam hidup sehari-hari (*bukan
teori) sehingga kelak keberadaan/ kehadiran diri dapat diterima dengan
senang hati (bahagia) oleh semua pihak dalam keadaan “ngaraga jeung ngawaruga”(menjelma
dan menghadirkan). Hal ini merupakan pola dasar pembentukan perilaku
manusia yang dilandasi oleh kesadaran rasa dan pikiran. Seseorang yang
telah mencapai tingkatan ini disebut “Dewa-Ta”.
- Dharma Raja, adalah mendidik diri untuk menghadirkan “Jati Diri” sebagai manusia “welas-asih” yang
seutuhnya dalam segala perilaku kehidupan “memberi tanpa diberi” atau
memberi tanpa menerima (tidak ada pamrih). Tingkatan ini merupakan
pencapaian derajat manusia paling terhormat yang patut dijadikan
suri-teladan bagi semua pihak serta layak disebut (dijadikan) pemimpin.
Ajaran Sunda berlandas kepada sifat bijak-bajik Matahari yang
menerangi dan membagikan cahaya terhadap segala mahluk di penjuru Bumi
tanpa pilih kasih dan tanpa membeda-bedakan. Matahari telah menjadi
sumber utama yang mengawali kehidupan penuh suka cita, dan tanpa
Matahari segalanya hanyalah kegelapan. Oleh sebab itulah para penganut
ajaran Sunda
berkiblat kepada Matahari (Sang Hyang Tunggal) sebagai simbol ketunggalan dan kemanunggalan yang ada di langit, dan
kiblatagama Sunda itu bukan diciptakan oleh manusia.
Sundayana menyebar ke seluruh dunia, terutama di wilayah
Asia, Eropa, Amerika dan Afrika, sedangkan di Australia tidak terlalu
menampak. Oleh masyarakat Barat melalui masing-masing kecerdasan kode
berbahasa mereka ajaran Matahari ini diabadikan dalam sebutan
SUNDAY (hari Matahari), berasal dari kata “Sundayana”
dan bangsa Indonesia lebih mengenal
Sundayitu sebagai hari Minggu.
Di wilayah Amerika kebudayaan suku Indian, Maya dan Aztec pun tidak
terlepas dari pemujaan kepada Matahari, demikian pula di wilayah Afrika
dan Asia, singkatnya hampir seluruh bangsa di dunia mengikuti ajaran
leluhur bangsa Galuh Agung (Nusantara) yang berlandaskan kepada
tata-perilaku berbudhi dengan rasa
“welas-asih” (cinta-kasih).
Jejak keberadaan ajaran agama Sunda yang kemudian berkembang hingga
saat ini terekam dalam kebudayaan masyarakat Roma (kerajaan Romawi) yang
menetapkan tanggal 25 Desember sebagai “Hari Matahari”
(Sunday) yaitu hari pemujaan kepada Matahari (Sunda) dan kini masyarakat Indonesia lebih mengenalnya sebagai hari “Natal”.
Oleh bangsa Barat (Eropa dan Amerika) istilah
Sundayana‘dirobah’ menjadi
Sunday sedangkan di Nusantara dikenal dengan sebutan “Surya” (*Bangsa Arya ?) yang berasal dari tiga suku kata yaitu
Su-Ra-Yana, bangsa Nusantara memperingatinya dalam upacara “Sura” (
Suro)
yang intinya bertujuan untuk mengungkapkan rasa menerima-kasih serta
ungkapan rasa syukur atas “kesuburan” negara yang telah memberikan
kehidupan dalam segala bentuk yang menghidupkan; baik berupa makanan,
udara, air, api (kehangatan), tanah, dan lain sebagainya.
Pengertian
Surayana pada hakikatnya sama saja dengan
Sundayana sebab mengandung maksud dan makna yang sama.
- SU = Sejati
- RA = Sinar/ Maha Cahaya/ Matahari
- YANA =
way of life/ ajaran/ ageman/ agama
Maka arti
“Surayana” adalah sama dengan “Agama Matahari
yang Sejati”
dan dikemudian hari bangsa Indonesia mengenal dan mengabadikannya
dengan sebutan “Sang Surya” untuk mengganti istilah “Matahari”.
Perobahan istilah “Sunda”
Sekilas gambaran di atas boleh jadi hanya bersifat
gatuk(mencocok-cocokan),
namun mustahil jika kemiripan penanda (sebutan dan objek) itu terjadi
dengan sendirinya tanpa sebab, selain itu terjadi pula kemiripan pada
nilai-nilai yang bersifat prinsip dan mustahil pula jika tidak ada yang
memulai dan mengajarkannya. Tentu “tidak mungkin ada akibat jika tanpa
sebab” (hukum aksi-reaksi), dalam pepatah leluhur bangsa Nusantara
menyebutkan “tidak ada asap jika tidak ada api” atau “mustahil ada
ranting jika tidak ada dahan” maka segalanya pasti ada yang memulai dan
mengajarkan.
5000 tahun sebelum penanggalan Masehi di Asia dalam sejarah peradaban bangsa Mesir
kuno menerangkan
(menggambarkan) tentang keberadaan ajaran Matahari dari bangsa Galuh,
mereka menyebutnya sebagai “RA” yang artinya adalah Sinar/ Astra/
Matahari/ Sunda.
“RA” digambarkan dalam bentuk “mata” dan diposisikan sebagai “Penguasa Tertinggi” dari seluruh ‘dewa-dewa’ bangsa Mesir
kunoyang lainnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bangsa Mesir
kuno-pun menganut dan mengakui
Sundayana (Agama Matahari) yang dibawa dan diajarkan oleh leluhur bangsa Galuh.
Disisi lain bangsa Indonesia saat ini mengenal bentuk dan istilah “mata”
(eye) yang mirip dengan gambaran “AMON-RA” bangsa Mesir
kuno, sebutan
“amon” mengingatkan kita kepada istilah
“panon” yang berarti “mata” yang terdapat pada kata
“Sang Hyang Manon” yaitu penamaan lain bagi Matahari di masyarakat Jawa Barat jaman dahulu (*apakah kata
Amon dan
Manonmemiliki makna yang sama?)
Selain di Asia (Mesir) bangsa Indian di Amerika-pun sangat memuja
Matahari (sebagai simbol leluhur, dan mereka menyebut dirinya sebagai
bangsa “kulit merah”) bahkan masyarakat Inca, Aztec dan Maya di daerah
Amerika
latin membangun kuil pemujaan yang khusus ditujukan
bagi Matahari, hingga mereka menggunakan pola penghitungan waktu yang
berlandas pada peredaran Matahari, mirip dengan di Nusantara (pola
penanggalan
Saka = Pilar Utama = Inti / Pusat Peredaran = Matahari).
Masyarakat suku Inca di Peru (Amerika Latin) membangun tempat pemujaan kepada Matahari di puncak bukit yang disebut
Machu Picchu. Dalam
hal ini terlihat jelas bahwa secara umum konsep “meninggikan dengan
pondasi yang kokoh” dalam kaitannya dengan “keagungan“ (tinggi, luhur,
puncak, maha) merupakan landas berpikir yang utama agama Sunda.
Secara filosofis, pola bentuk ‘bangunan’ menuju puncak meruncing
(gunungan) itu merupakan perlambangan para Hyang yang ditinggikan atau
diluhurkan, hal inipun merupakan silib-siloka tentang perjalanan manusia
dari “ada” menuju “tiada” (langit), dari
jelma menjadi manusia utama hingga kelak menuju puncak kualitas manusia adiluhung (maha agung).
Demikian pula yang dilakukan oleh suku Maya di Mexico pada jaman
dahulu, mereka secara khusus membangun tempat pemujaan (kuil/pura)
kepada Matahari (Sang Hyang Tunggal).
Pada jaman dahulu hampir seluruh bangsa di benua Amerika (penduduk
asli) memuja kepada Matahari, dan hebatnya hampir semua bangsa
menunjukan hasil kebudayaan yang tinggi. Kemajuan peradaban dalam bidang
arsitektur, cara berpakaian, sistem komunikasi (baik bentuk lisan,
tulisan, gaya bahasa, serta gambar), adab upacara, dll. Kemajuan dalam
bidang pertanian dan peternakan tentu saja yang menjadi yang paling
utama, sebab hal tersebut menunjukan kemakmuran masyarakat, artinya
mereka dapat hidup sejahtera tentram dan damai dalam kebersamaan hingga
kelak mampu melahirkan keindahan dan keagungan dalam berkehidupan
(berbudaya).
Sekitar abad ke XV kebudayaan agung bangsa Amerika
latinmengalami keruntuhan setelah datangnya para
missionaris Barat yang membawa misi
Gold, Glory dan
Gospel. Tujuan utamanya tentu saja
Gold (emas/ kekayaan) dan
Glory (kejayaan/ kemenangan) sedangkan
Gospel (agama) hanya dijadikan sebagai kedok politik agar seolah-olah mereka bertujuan untuk “memberadabkan” sebuah bangsa.
Propaganda yang mereka beritakan tentang perilaku biadab agama
Matahari dan kelak dipercaya oleh masyarakat dunia adalah bahwa; “suku
terasing penyembah matahari itu pemakan manusia”, hal ini mirip dengan
yang terjadi di Sumatra Utara serta wilayah lainnya di Indonesia.
Dibalik propaganda tersebut maksud sesungguhnya kedatangan para
‘penyebar agama’ itu adalah perampokan kekayaan alam dan perluasan
wilayah jajahan
(imperialisme), sebab mustahil bangsa yang sudah
“beragama” harus ‘diagamakan’ kembali dengan ajaran yang tidak
berlandas kepada nilai-nilai kebijakan dan kearifan lokalnya.
Dalam pandangan penganut agama Sunda (bangsa Galuh) yang dimaksud
dengan “peradaban sebuah bangsa (negara)” tidak diukur berdasarkan
nilai-nilai material yang semu dan dibuat-buat oleh manusia seperti
bangunan megah, emas serta batu permata dan lain sebagainya melainkan
terciptanya keselarasan hidup bersama alam (keabadian). Prinsip tersebut
tentu saja sangat bertolak-belakang dengan negara-negara lain yang
kualitas geografisnya tidak sebaik milik bangsa beriklim tropis seperti
di Nusantara dan negara tropis lainnya. Leluhur Galuh mengajarkan
tentang prinsip kejayaan dan kekayaan sebuah negara sebagai berikut :
“Gunung kudu pageuh, leuweung kudu hejo, walungan kudu herang, taneuh kudu subur, maka bagja rahayu sakabeh rahayatna”
(Gunung harus kokoh, hutan harus hijau, sungai harus jernih, tanah harus subur, maka tentram damai sentausa semua rakyatnya)
“Gunung teu meunang dirempag, leuweung teu meunang dirusak”
(Gunung tidak boleh dihancurkan, hutan tidak boleh dirusak)
Kuil (tempat peribadatan) pemujaan Matahari hampir seluruhnya
dibangun berdasarkan pola bentuk “gunungan” dengan landasan segi empat
yang memuncak menuju satu titik. Boleh jadi hal tersebut berkaitan erat
dengan salah satu pokok ajaran Sunda dalam mencapai puncak kualitas
bangsa (negara) seperti Matahari yang bersinar terang, atau sering
disebut sebagai
“Opat Ka Lima Pancer” yaitu; empat unsur inti alam (Api, Udara, Air, Tanah) yang memancar menjadi “gunung” sebagai sumber kehidupan mahluk.
Menilik bentuk-bentuk simbolik serta orientasi pemujaannya maka dapat
dipastikan bahwa piramida di wilayah Mesir-pun sesungguhnya merupakan
kuil Matahari
(Sundapura). Walaupun sebagian ahli sejarah
mengatakan bahwa piramid itu adalah kuburan para raja namun perlu
dipahami bahwa raja-raja Mesir
kuno dipercaya sebagai; Keturunan
Matahari/ Utusan Matahari/ Titisan Matahari/ ataupun Putra Matahari,
dengan demikian mereka setara dengan “Putra Sunda”(Utusan Sang Hyang
Tunggal).
Untuk sementara istilah “Putra Sunda” bagi para raja Mesir
kunodan
yang lainnya tentu masih terdengar janggal dan aneh sebab selama ini
sebutan “Sunda” selalu dianggap sebagai suku, ras maupun wilayah kecil
yang ada di pulo Jawa bagian barat saja, istilah “Sunda” seolah tidak
pernah terpahami oleh bangsa Indonesia pun oleh masyarakat Jawa Barat
sendiri.
Tidak diketahui waktunya secara tepat, Sang Narayana Galuh Hyang Agung
(Galunggung) mengembangkan
dan mengokohkan ajaran Sunda di Jepang, dengan demikian RA atau
Matahari begitu kental dengan kehidupan masyarakat Jepang, mereka
membangun tempat pemujaan bagi Matahari yang disebut sebagai Kuil
Nara (Na-Ra / Api-Matahari) dan masyarakat Jepang dikenal sebagai pemuja
Dewi Amate-Ra-Su Omikami yang digambarkan sebagai wanita bersinar
(Astra / Aster / Astro / Astral / Austra).
Tidak hanya itu, penguasa tertinggi “Kaisar Jepang” pun dipercaya sebagai titisan Matahari atau Putra Matahari
(Tenno) dengan
kata lain para kaisar Jepang-pun bisa disebut sebagai “Putra Sunda”
(Anak/ Utusan/ Titisan Matahari) dan hingga saat ini mereka
mempergunakan Matahari sebagai lambang kebangsaan dan kenegaraan yang
dihormati oleh masyarakat dunia.
Dikemudian hari Jepang dikenal sebagai negeri “Matahari Terbit” hal
ini disebabkan karena Jepang mengikuti jejak ajaran leluhur bangsa
Nusantara, hingga pada tahun 1945 ketika pasukan Jepang masuk ke
Indonesia dengan misi “Cahaya Asia” mereka menyebut Indonesia sebagai
“Saudara Tua” untuk kedok politiknya.
Secara mendasar ajaran para leluhur bangsa Galuh dapat diterima di
seluruh bangsa (negara) karena mengandung tiga pokok ajaran yang
bersifat universal (logis dan realistis), tanpa tekanan dan paksaan
yaitu :
- Pembentukan nilai-nilai pribadi manusia (seseorang) sebagai landasan
pokok pembangunan kualitas keberadaban sebuah bangsa (masyarakat) yang
didasari oleh nilai-nilai welas-asih (cinta-kasih).
- Pembangunan kualitas sebuah bangsa menuju kehidupan bernegara yang
adil-makmur-sejahtera dan beradab melalui segala sumber daya bumi (alam/
lingkungan) di wilayah masing-masing yang dikelola secara bijaksana
sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari.
- Pemeliharaan kualitas alam secara selaras yang kelak menjadi pokok
kekayaan atau sumber daya utama bagi kehidupan yang akan datang pada
sebuah bangsa, dan kelak berlangsung dari generasi ke generasi
(berkelanjutan).
Demikian ajaran Sunda (
Sundayana/
Surayana/ Agama
Matahari) menyebar ke seluruh penjuru Bumi dibawa oleh para Guru Hyang
memberikan warna dalam peradaban masyarakat dunia yang diserap dan
diungkapkan (diterjemahkan) melalui berbagai bentuk tanda berdasarkan
pola kecerdasan masing-masing bangsanya.
Ajaran Sunda menyesuaikan diri dengan letak geografis dan watak
masyarakatnya secara selaras (harmonis) maka itu sebabnya bentuk
bangunan suci (tempat pemujaan) tidak menunjukan kesamaan disetiap
negara, tergantung kepada potensi alamnya. Namun demikian pola dasar
bangunan dan filosofinya memiliki kandungan makna yang sama, merujuk
kepada bentuk gunungan.
Di Indonesia sendiri simbol “RA” (Matahari/ Sunda) sebagai ‘penguasa’
tertinggi pada jaman dahulu secara nyata teraplikasikan pada berbagai
sisi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Hal itu diungkapkan dalam
bentuk (rupa) serta penamaan yang berkaitan dengan istilah “RA”
(Matahari) sebagai sesuatu yang sifat agung maupun baik, seperti;
- Konsep wilayah disebut “Naga-Ra/ Nega-Ra”
- Lambang negara disebut “Bende-Ra”
- Maharaja Nusantara bergelar “Ra-Hyang”
- Keluarga Kerajaan bergelar “Ra-Keyan dan Ra-Ha-Dian (Raden)”.
- Konsep ketata-negaraan disebut “Ra-si, Ra-tu, Ra-ma”
- Penduduknya disebut “Ra-Hayat” (rakyat).
- Nama wilayah disebut “Dirganta-Ra, Swarganta-Ra, Dwipanta-Ra, Nusanta-Ra, Indonesia (?)”
dll.
Kemaharajaan (Keratuan/ Keraton) Nusantara yang terakhir, “Majapahit” kependekan dari
Maharaja-Pura-Hita (Tempat Suci Maharaja
yang Makmur-Sejahtera)
dikenal sebagai pusat pemerintahan “Naga-Ra” yang terletak di Kadiri –
Jawa Timur sekitar abad XIII masih mempergunakan bentuk lambang
Matahari, sedangkan dalam panji-panji kenegaraan lainnya mereka
mempergunakan warna “merah dan putih”
(Purwa-Daksina) yang serupa dengan pataka (‘bendera’) Indonesia saat ini.
Bende – Ra Majapahit
Tidak terlepas dari keberadaan ajaran Sunda (Matahari) dimasa lalu
yang kini masih melekat diberbagai bangsa sebagai lambang kenegaraan
ataupun hal-hal lainnya yang telah berobah menjadi legenda dan
mithos,
tampaknya bukti terkuat tentang cikal-bakal (awal) keberadaan ajaran
Matahari atau agama “Sunda” itu masih tersisa dengan langgeng di Bumi
Nusantara yang kini telah beralih nama menjadi Indonesia.
Di Jawa
Kulon (Barat) sebagai wilayah suci tertua
(Mandala Hyang) tempat bersemayamnya Leluhur Bangsa Matahari
(Pa-Ra-Hyang) hingga saat ini masih menyisakan penandanya sebagai pusat ajaran Sunda (Matahari), yaitu dengan ditetapkannya kata
“Tji” (Ci) yang artinya CAHAYA di berbagai wilayah seperti;
Ci Beureum (Cahaya Merah),
Ci Hideung (Cahaya Hitam),
Ci Bodas(Cahaya Putih),
Ci Mandiri (Cahaya
Mandiri), dan lain sebagainya. Namun sayang banyak ilmuwan Nusantara
khususnya dari Jawa Barat malah menyatakan bahwa “Ci” adalah
“cai” yang
diartikan sebagai “air”, padahal jelas-jelas untuk benda cair itu
masyarakat Jawa Barat jaman dulu secara khusus menyebutnya sebagai
“Banyu” dan sebagian lagi menyebutnya sebagai
“Tirta” (*belum diketahui perbedaan diantara keduanya).
Sebutan “Ci” yang kelak diartikan sebagai “air”
(cai/nyai)sesungguhnya berarti “cahaya/ kemilau” yang terpantul di permukaan
banyu (tirta) akibat
pancaran “sinar” (kemilau). Masalah “penamaan/ sebutan” seperti ini
oleh banyak orang sering dianggap sepele, namun secara prinsip berdampak
besar terhadap “penghapusan” jejak perjalanan sejarah para leluhur
bangsa Galuh Agung pendiri agama Sunda (Matahari).
`Cag
Rampes,,,


 Agar
lebih jelas kita gunakan contoh sebagai berikut; jika seseorang
mengatakan “Saya orang Indonesia beragama Islam” (*Islam = Selamat)
pernyataan itu sering disingkat menjadi “Saya orang Islam”. Lain hal
jika kalimatnya berbunyi “Saya bangsa Indonesia menganut agama Islam”,
dalam kalimat tersebut jelas mengatakan status kebangsaannya, dan memang
tidak ada “bangsa Islam” di Indonesia sebab yang layak disebut “bangsa
Islam” tentunya hanya bangsa Arab itu sendiri. Maka demikian pula dengan
persoalan Sunda dan Galuh, hingga dengan sewajarnya jika mengatakan
bahwa “Saya orang Galuh beragama Sunda”.
Agar
lebih jelas kita gunakan contoh sebagai berikut; jika seseorang
mengatakan “Saya orang Indonesia beragama Islam” (*Islam = Selamat)
pernyataan itu sering disingkat menjadi “Saya orang Islam”. Lain hal
jika kalimatnya berbunyi “Saya bangsa Indonesia menganut agama Islam”,
dalam kalimat tersebut jelas mengatakan status kebangsaannya, dan memang
tidak ada “bangsa Islam” di Indonesia sebab yang layak disebut “bangsa
Islam” tentunya hanya bangsa Arab itu sendiri. Maka demikian pula dengan
persoalan Sunda dan Galuh, hingga dengan sewajarnya jika mengatakan
bahwa “Saya orang Galuh beragama Sunda”.




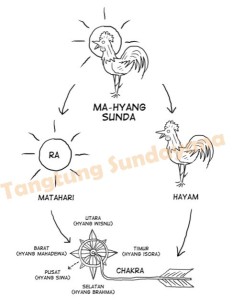

























 Sepiring bertiga, nyiapin perut untuk Tutut
Sepiring bertiga, nyiapin perut untuk Tutut





